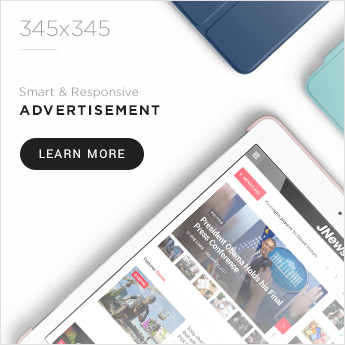Matahari belum sepenuhnya naik ketika kami meninggalkan Puskesmas Sarudu 2. Waktu baru menunjukkan pukul 07.00 WITA, udara pagi terasa lembap, dan jalanan tanah yang semalam gelap kini menampakkan warna hitam aspal dan berapa titik nampak bekas timbunan tanah. Kami bersiap kembali ke Mamuju, menempuh ratusan kilometer jalan yang sama panjangnya dengan cerita yang kami bawa.
Di perjalanan menuju jalan Trans Sulawesi dari Bulumario ke Simpang tiga Tanamoni tepatnya di Desa Kumasari, kami melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Spanduk biru yang sepertinya masih baru bertuliskan Warung Mbah Bagio. Plang kayunya sederhana, catnya mulai pudar, tapi aroma yang keluar dari warung itu membuat kami berhenti tanpa banyak bicara.
“Ayo kita Singgah dulu sarapan,” kata Pak Madur sambil tersenyum.
Warung itu milik seorang perempuan paruh baya yang kami panggil Mbak, panggilan kebiasaan bagi wanita suku Jawa. Di meja panjang, ada wadah prasmanan hijau berisi sayur matang, dan lauk pauk sederhana seperti telur rebus, ikan goreng, ayam kuah, tempe campur sayur. Kami memesan dua porsi nasi kuning dan duduk di bangku kayu yang mulai kusam warnanya karena sering tersentuh hujan dan panas.
Sambil menunggu, Mbak Bagio bercerita. Suaranya lembut tapi tegas, khas orang Jawa yang sudah lama hidup di tanah perantauan.
“Dua tahun terakhir saya jualan di sini saja, depan rumah,” katanya sambil menuang sambal di piring kami. “Dulu jualnya di sekolah dan saya berhenti karena focus urus anak-anak, tapi banyak yang minta buka warung tetap, ya akhirnya buka saja di sini.”
Pak Madur menimpali sambil tersenyum, “Sudah lama di sini, Mbah?”
Mbah Bagio tertawa kecil. “Baru, Mas… baru 32 tahun.”
Tawa kami pecah bersamaan. Logat Jawanya terdengar lincah dan hangat. Ia lalu bercerita bahwa ia dan keluarganya berasal dari Jawa Tengah, datang ke Sulawesi lewat program transmigrasi tahun 1992. “Dulu kami ditempatkan di sini dengan lahan perumahan 50 x 100 meter. Waktu itu masih hutan, jalan belum seperti sekarang,” kenangnya.
Cerita tentang transmigrasi seperti milik Mbak Bagio bukan hal baru di wilayah ini. Di Pasangkayu, khususnya Sarudu, desa-desa dengan kode SP (Satuan Pemukiman) adalah hasil dari program besar pemerintah untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah pada era 1980–1990an.
Banyak keluarga dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang menetap di tanah ini. Mereka membuka lahan, membangun rumah, dan membentuk komunitas kecil dengan budaya yang perlahan berbaur dengan masyarakat lokal.
Kini, setelah tiga dekade, generasi kedua dan ketiga transmigran tumbuh bersama masyarakat setempat. Jalanan yang dulu tanah dan jalan setapak kini sudah beraspal, meski masih ada lubang di sana-sini. Tapi di warung sederhana seperti milik Mbak Bagio, kita bisa merasakan perpaduan antara kenangan masa lalu dan semangat bertahan hidup yang tak pernah padam.
Nasi kuning buatan Mbak Bagio sederhana tapi memikat. Nasinya pulen, bumbu ikannya terasa, sambalnya tidak terlalu pedas tapi menambah selera. Setiap suapan seperti menyimpan kehangatan rumah yang jauh, entah itu di Jawa atau di Kumasari.
“Kalau pagi ramai, Mas. Banyak yang kerja di kebun mampir dulu makan,” katanya sambil mengisi ulang cerek air untuk kami minum. Kami makan pelan-pelan, menikmati udara pagi yang mulai hangat. Tak ada musik, tak ada suara kendaraan besar. Hanya obrolan ringan dan bunyi sendok menyentuh piring. Di tengah perjalanan panjang, warung kecil seperti ini terasa seperti jeda yang penuh makna.
Ketika kami berpamitan, Mbak Bagio tersenyum dan melambaikan tangan. Warung kecil itu kembali sunyi. Tapi di sana, di antara aroma nasi kuning dan tawa yang singkat, tersimpan jejak panjang sebuah kebijakan besar yang kini menjelma jadi keseharian warga. Transmigrasi tak lagi sekadar program pemerintah. Ia telah menjadi kisah manusia, kisah tentang adaptasi, kerja keras, dan kemampuan bertahan di tanah baru.
Di mobil, saat kembali melaju ke arah Trans Sulawesi, saya teringat ucapan Mbak Bagio yang ringan tapi dalam.
“Orang datang jauh-jauh ke sini, Mas. Sekarang, kalau nggak jualan, malah kangen ramai-ramai orang beli nasi kuningnya.”
Kadang, perubahan besar tidak hanya lahir di kantor pemerintahan atau ruang rapat. Ia juga tumbuh diam-diam di warung kecil pinggir jalan, tempat di mana nasi kuning, sambal, dan tawa bisa menjadi penanda bahwa kehidupan terus berjalan, 32 tahun dan rasanya masih seperti baru kemarin.