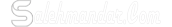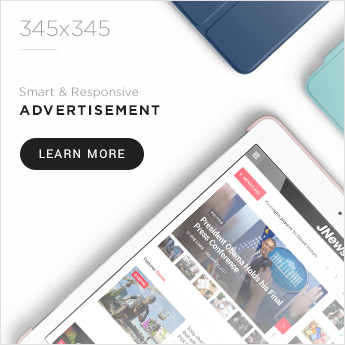Setiap tanggal 10 Juni, Indonesia memperingati Hari Media Sosial. Di tengah lalu lintas unggahan yang nyaris tanpa henti, peringatan ini sering kali hanya menjadi penanda simbolik, sekadar pengingat bahwa kita hidup dalam zaman ketika satu jempol bisa lebih berbahaya dari sejuta kata. Namun, lebih dari itu, momen ini seharusnya menjadi refleksi kolektif: bagaimana kita, sebagai warga digital, memperlakukan ruang maya yang makin liar, bising, dan penuh jebakan.
Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi. Ia memangkas batas ruang dan waktu, membuka ruang ekspresi, menghidupkan solidaritas digital, hingga menggulingkan kekuasaan. Tetapi seperti dua sisi mata uang, media sosial juga membawa kerentanan, dari hoaks yang tak kunjung reda, polarisasi politik, perundungan daring, hingga praktik doxing yang mengancam privasi dan keamanan.
Indonesia adalah salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia. Data We Are Social 2025 mencatat bahwa lebih dari 70% populasi Indonesia aktif di media sosial. TikTok, Instagram, dan WhatsApp menjadi favorit, terutama di kalangan muda. Ini tentu prestasi, tapi sekaligus tantangan.
Di balik angka itu, ada potret buram: Indonesia termasuk negara dengan tingkat penyebaran hoaks tertinggi di Asia Tenggara. Di tahun politik seperti sekarang, polarisasi makin terasa. Media sosial yang semestinya menjadi jembatan dialog justru berubah menjadi medan pertempuran opini. Bahkan, tak jarang, komentar nyinyir lebih cepat viral ketimbang gagasan bernas.
Algoritma yang seharusnya membantu pengguna menemukan informasi yang relevan malah menjebak dalam gelembung informasi. Akibatnya, orang lebih suka dibenarkan daripada diberi kebenaran.
Tagar #SaringSebelumSharing sudah sering kita lihat. Tapi ironisnya, justru yang menyebarkan hoaks sering adalah orang-orang terdekat: keluarga, sahabat, bahkan tokoh panutan. Ini bukan semata soal literasi digital yang rendah, tapi juga karena budaya kritis yang belum tumbuh kuat.
Mengapa kita begitu mudah membagikan sesuatu tanpa cek fakta? Mungkin karena kita terburu-buru ingin menjadi yang pertama tahu. Mungkin karena kita senang merasa benar. Mungkin juga karena kita terlalu percaya bahwa niat baik tak perlu verifikasi. Padahal, dalam dunia digital, niat baik tanpa akal sehat bisa berujung petaka.
Hari Media Sosial seharusnya tak hanya menjadi selebrasi, melainkan juga ajakan. Ajakan untuk berbenah, untuk lebih bijak, untuk lebih kritis. Menjadi warga digital bukan hanya soal eksis, tapi juga soal etis. Etika digital seharusnya diajarkan sejak dini, sebagaimana kita diajarkan untuk menyapa orang tua dengan sopan.
Kita perlu berhenti menganggap media sosial hanya sebagai hiburan. Ia adalah ruang publik, dan di ruang publik, tanggung jawab moral tak bisa ditinggalkan di depan layar. Setiap unggahan punya dampak. Setiap komentar bisa melukai. Dan setiap share yang sembrono bisa menyalakan api yang sulit dipadamkan.
Hari Media Sosial adalah waktu yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri: sudahkah saya menggunakan media sosial dengan bijak? Atau jangan-jangan saya bagian dari masalah itu sendiri?
Di era ketika jempol bisa lebih tajam dari pedang, mari kita gunakan akal sehat sebagai filter utama. Karena di ujung hari, media sosial bukan soal seberapa banyak yang kita bagikan, tapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan.