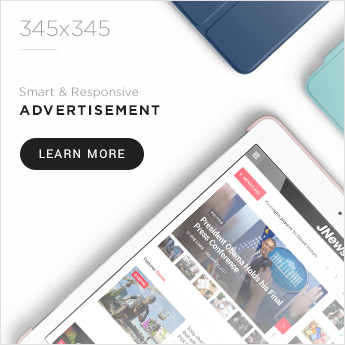Jam menunjukkan pukul 04.16 dini hari ketika saya meninggalkan pos Satkamling di perempatan lorong tempat kami tinggal. Udara masih lembab, embun mulai turun, dan suara alunan mengaji dari masjid tak jauh dari rumah mulai terdengar samar. Di pos ronda, beberapa cangkir kopi masih mengepulkan sisa hangatnya di atas meja kayu. Sambil menunggu sholat subuh saya mengetik cerita ini sambil menunggu adzan subuh berkumandang.
–
Setiap malam, sekitar 15-20 orang bapak-bapak lorong bergiliran menempati tenda sederhana yang kami jadikan pos ronda. Biasanya mulai ramai sejak pukul delapan atau sembilan malam. Ada jadwal tak resmi yang terpasang di tembok rumah pak RT, namun tak ada absensi. Tapi setiap malam, selalu saja ada yang datang entah membawa cerita, rokok, atau sekadar ingin meneguk kopi bersama.
Bagi sebagian orang kota, pos Satkamling mungkin hanya papan nama di ujung gang. Tapi bagi kami, ini adalah nadi kebersamaan warga. Di sinilah koordinasi keamanan dibicarakan, isu-isu kecil lingkungan dibahas, dan yang lebih penting warga belajar untuk saling menjaga.
Ronda malam bukan sekadar menghalau maling. Ia menjadi cara sederhana menciptakan rasa aman dan membangun trust di antara tetangga, sesuatu yang mulai langka di banyak kompleks perumahan modern yang kini lebih mengandalkan CCTV daripada komunikasi.
Malam ini saya bergabung di pos ronda sekitar pukul 21.30 WITA, setelah istirahat sejenak usai salat Isya. Seperti 2 pekan lalu, saya membawa nampang berisi pisang goreng dan ubi jalar goreng, plus satu termos besar kopi susu. Kebetulan, malam ini juga giliran keluarga saya menyiapkan snack bersama empat keluarga lainnya.
Di bawah cahaya lampu sorot yang agak temaram, dua meja dipenuhi bapak-bapak yang sedang asyik bermain kartu remi. Tawa dan gurauan mengalir ringan. Pak RT dan Pak Lingkungan ikut duduk, membaur tanpa jarak. Di sini, jabatan ditanggalkan, yang tersisa hanyalah suasana guyub khas warga kampung.
Sekitar pukul 11 malam, saya bersama Papa Ani dan Ustaz Ali mulai berkeliling kompleks. Kami memeriksa pintu-pintu pagar, memastikan tidak ada motor terparkir di tempat sepi, dan menengok beberapa rumah yang lampunya masih menyala.
Di sela langkah, percakapan kecil mengalir.
“Rumah itu milik siapa, Pa?” tanya Ustaz Ali, yang baru beberapa tahun ini pindah ke lorong kami.
“Itu rumahnya Pak ini, orang tuanya pemilik tanah sampai ke mesjid dan rencananya mau di jual per kapling,” jawab Papa Ani pelan sambil menunjuk rumah dengan pekarangan yang luas.
Dari satu rumah ke rumah lain, Papa Ani seolah menjadi peta hidup lorong kami. Ia tahu siapa pemilik setiap rumah, siapa yang sedang merantau, bahkan siapa keluarga yang punya dan belum punya anak.
Sekitar pukul dua dini hari, kami kembali berkeliling bersama Pak Haris, seorang ASN dari Kementerian Agama yang sering jadi bahan cerita karena kisah perjalanannya dari Pulau Alor ke Mamuju. Malam itu, langkah kami diiringi obrolan ringan tentang banyak hal mulai dari rencana pemasangan CCTV di tiap pintu masuk, ide membuat sistem keamanan terpadu, sampai pembahasan tentang upacara Hari Sumpah Pemuda besok, 28 Oktober.
Menjelang pukul 2.30, sebagian besar bapak-bapak mulai pamit. Rasa kantuk dan lelah mulai menyerang. Satu per satu mereka pulang, digantikan oleh anak-anak muda yang datang membawa energi baru. Mereka duduk di salah satu meja, menyiapkan papan domino, dan mulai tertawa keras di sela-sela permainan.
Saya sesekali membaringkan tubuh di meja kayu, mencoba mencuri waktu untuk memejamkan mata beberapa menit. Tapi suara tawa para pemuda dan denting domino yang jatuh membuat saya tetap terjaga. Dalam kantuk yang menggantung, saya merasa lega karena ronda malam ini tidak hanya dijaga oleh para bapak, tapi mulai diwarisi oleh generasi muda.
Di luar sana, banyak kompleks mengandalkan teknologi berupa kamera pengintai, pagar otomatis, bahkan patroli keamanan berbayar. Tapi di lorong kecil kami, keamanan dibangun lewat kebersamaan. Kami saling mengenal, saling menitipkan rumah, dan saling berbagi makanan serta waktu.
Menjelang Subuh, saya meninggalkan pos ronda dengan langkah pelan. Di belakang saya, suara Pak Ilham dan Papa Ani masih terdengar. Kopi terakhir sudah dingin, tapi hangatnya kebersamaan masih tersisa di dada.
Di lorong kecil ini, kami belajar satu hal sederhana bahwa rasa aman bukan hanya hasil dari penjagaan, tapi dari kebersamaan yang terus dijaga.