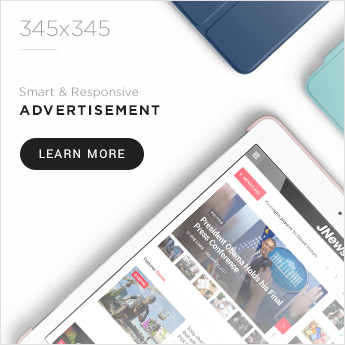Setelah serangkaian diskusi santai tentang digitalisasi kesehatan, kami melangkah ringan menuju sebuah jembatan gantung yang menjadi penghubung lama di tengah bentang alam Kalumpang. Di kejauhan, Gunung Paken berdiri megah seperti penjaga sunyi yang tak pernah lelah mengawasi. Di puncaknya, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Paken, desa di atas langit yang dulu hanya terdengar dalam cerita-cerita warga.
Setelah serangkaian diskusi santai tentang digitalisasi kesehatan, kami melangkah ringan menuju sebuah jembatan gantung yang menjadi penghubung lama di tengah bentang alam Kalumpang. Di kejauhan, Gunung Paken berdiri megah seperti penjaga sunyi yang tak pernah lelah mengawasi. Di puncaknya, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Paken, desa di atas langit yang dulu hanya terdengar dalam cerita-cerita warga.
Jembatan gantung itu sendiri telah berubah. Lantai kayu yang dulu rapuh kini diganti dengan baja ringan. Tapi gemuruh sungai di bawahnya tetap sama. Deras, dingin, dan jernih. Di pinggirannya, perahu kecil “kalotok” masih setia bersandar, seperti tak pernah terusik waktu.
Saya duduk sejenak, membiarkan suara sungai dan desir angin menerpa wajah. Kalumpang sore ini adalah pertemuan antara alam, waktu, dan perasaan yang tak bisa dituliskan hanya dengan data dan angka capaian program.
Langit mulai menguning keemasan. Lapangan bola sederhana di tengah kampung menjadi pusat semesta sore ini. Anak-anak muda bermain voli penuh semangat, menggiring bola dengan tawa dan peluh.
Pemandangan yang unik membingkai lapangan itu, sebuah gereja tua berdiri di atas bukit. Ia tak hanya menjadi penanda keyakinan, tapi juga simbol harmoni dalam keberagaman yang tenang di tanah Kalumpang. Tak ada hiruk-pikuk, hanya kehidupan yang berjalan selaras, senyap namun hangat.
Menjelang magrib, langkah kaki membawa saya ke Masjid Alquba. Saya pernah beberapa kali sholat di sini dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya. Kali ini, masjid itu tampak berbeda lantainya sudah berkeramik, dan atapnya bergaya modern. Tapi keheningan dan keintiman tempat ibadah ini tetap utuh.
Imam tidak hadir malam itu. Tanpa banyak kata, saya didaulat menjadi imam. Ada tiga orang berdiri di belakang saya. Kalumpang agak sepi karena banyak warga tengah berkumpul di Karama, malam ini adalah malam lamaran bidan Puskesmas Karama dengan driver ambulans Puskesmas Kalumpang. Besok, mereka menikah.
Sholat di masjid kecil, bersama tiga orang jamaah, dikelilingi sunyi dan malam yang belum gelap benar, membawa saya pada renungan dalam. Ada rasa khidmat yang tak saya temui di masjid besar dan penuh jamaah di kota.
Malam menjemput, dan saya menginap di rumah Izzink, nama akrab dari Indra Ningsih, teman letting sekaligus rekan seasrama saya saat kuliah di Makassar belasan tahun lalu. Rumahnya sederhana tapi hangat, seperti biasa. Tak terasa, hampir 19 tahun telah berlalu sejak pertama kami saling kenal.
Saya juga bertemu dengan Risnanto, teman lama yang kini rambutnya telah memutih sebagian. Sebuah cermin kecil bahwa usia terus berjalan meski kita kerap lupa.
Malam setelah Isya berlalu , Desi teman seasrama di Kampus puluhan tahun lalu juga berkunjung bersama dengan anaknya yang seorang anak karate. Dengan anak yang sudah berusia 9 tahun, sama dengan usia anak pertama saya, Abdullah Azzam.
Namun di antara pertemuan, senyum, dan obrolan ringan, ada satu hal yang membuat perjalanan ini lebih istimewa dari sebelumnya, untuk pertama kalinya saya ke Kalumpang bersama seorang perempuan yang telah menancapkan cintanya di hati saya.
Tak perlu nama disebut, karena perasaan lebih fasih dalam diam.
Malam ditutup dengan makan malam sederhana, ayam kampung dimasak dengan bawang, merica, dan serai. Rasanya tak kalah dengan restoran mahal di kota, karena yang membumbui adalah tawa, cerita lama, dan kehangatan rumah.
Kalumpang, seperti biasa, tak pernah menyajikan gemerlap. Tapi ia selalu meninggalkan kesan yang tak bisa hilang begitu saja. Di antara jembatan gantung, sungai deras, lapangan kampung, dan masjid kecil saya menemukan sesuatu yang lebih penting dari capaian transformasi digital yaitu saya menemukan kembali bagian dari diri saya sendiri.
Dan malam ini, Kalumpang bukan lagi sekadar tempat di peta. Ia telah menjadi ruang kenangan yang akan saya bawa pulang dalam diam, dalam ingatan.